Ngejot: “Parsel” Khas Bali
Oleh Gede H.
Cahyana
Pejabat di SKPD DKI Jakarta dilarang
menerima parsel oleh Gubernur petahana dalam Pilkada DKI 2012. Terlepas dari
kebolehan menerima parsel setelah Ramadhan, tulisan ini fokus pada jenis parsel
yang justru diizinkan dikirimkan pada Ramadhan dan menjadi bagian tak
terpisahkan dari tradisi kehidupan muslimin di Bali.
Pasalnya,
parsel khas di Bali ini sudah terjadi puluhan atau bahkan ratusan tahun lalu, jauh mendahului
budaya parsel di kota-kota besar. Apalagi pengiriman parsel ini tidak berkaitan
dengan KKN tetapi sebagai penerus budaya toleransi di Bali. Parsel khas Bali
ini namanya ngejot.
Ngejot sudah lumrah. Bentuknya tidak seperti parsel modern di kota
besar yang dibuat dari wadah rotan dan dihias artistik. Motivasinya pun jauh
berbeda. Tidak seperti “parsel modern” yang ada udang di balik batu, terutama
yang nilainya berjuta-juta rupiah, parsel tradisional Bali nilainya tidak
terlalu tinggi. Paling mahal sekitar dua puluh ribu rupiah. Kenapa bisa semurah
itu? Sebab, yang diparselkan adalah makanan berupa nasi, sayur dan
lauk-pauknya. Ada juga ditambahi kue kering dan minuman ringan.
Aktivitas
bagi-bagi parsel yang disebut ngejot
itu dilakoni oleh umat Hindhu dan Islam. Yang diparselkan disebut jotan. Bagi orang Islam, fenomena ini adalah
modifikasi ngejot orang Hindu ketika menyambut hari raya Galungan dan Kuningan.
Sebelum Galungan, hari raya umat Hindhu yang selalu jatuh pada Rabu itu didahului
oleh beberapa prosesi. Yang pertama adalah pengejukan atau penangkapan babi.
Berikutnya adalah penampahan (pemotongan babi). Potong babi ini dilaksanakan
bersama-sama, baik antara tetangga maupun antara saudara sedarah seketurunan. Barulah
dilaksanakan pengejotan. Karena tahu umat Islam tidak boleh makan babi, maka yang dijot bianya kue dan buah-buahan.
Kalaupun ada nasi, tetapi
lauk-pauknya dari daging ayam.
Setelah ngejot,
kaum muslim siap-siap menyambut lebaran. Ada yang membuat kue dengan
mengerahkan anak-anak, cucu, kakek, nenek. Mereka bekerja terus, bahkan sampai
ada yang rela tidak puasa demi memasak yang begitu banyak. Tepat pada hari
lebaran, suasananya tidak seramai di Jawa
atau Madura. Yang lebih ramai adalah di objek wisata karena banyak dikunjungi
oleh wisatawan domestik yang berlibur ke Bali. Bahkan dua hari sebelum lebaran
banyak yang sudah tinggal di hotel dan melaksanakan salat Ied di sekitar hotel.
Malah ada hotel yang jelas-jelas mengakomodasi dan disertakan dalam promosi
wisatanya bahwa akan diadakan shalat Ied di dekat hotel.
Namun demikian,
di “kantong-kantong” Islam, katakanlah di Desa Pegayaman, ada kekecualian. Di
desa yang letaknya di bukit Kecamatan Sukasada ini mayoritas beragama Islam.
Bahkan diyakini seratus persen muslim. Dengan penduduk sekitar 6.000-an orang,
Pegayaman adalah mikrokomunitas khas muslim. Mereka berasal dari keturunan
prajurit Kerajaan Blambangan. Seperti muslim di daerah lain, mereka pun
melaksanakan serial budaya seperti penampahan (potong ayam, kambing), dll.
Fenomena serupa
terjadi di Desa Soka, di Selatan Gunung Batukaru Kecamatan Baturiti. Desa di
daerah dingin ini juga nyaris seratus persen beragama Islam. Seperti Pegayaman,
mereka pun berinteraksi dengan orang-orang Hindhu. Bahkan prosesi dalam menyambut
lebaran mirip dengan menyambut hari raya Galungan dan Kuningan. Misalnya,
sebelum lebaran kaum muslim membagikan makanan berupa nasi lengkap dengan
lauknya: ayam, daging sapi sisir (be sisit: bahasa Bali) dan sayur.
Siapa saja yang
dijot? Penerima jotan adalah orang Hindhu dan Kristen. Yang keliling membagikannya biasanya
anak-anak atau ibunya. Yang membuat kue dan masakan itu pun biasanya anak-anak,
baik laki maupun perempuan. Kesibukan ini sudah dilaksanakan seminggu sebelum
lebaran. Begitu pun sebaliknya, pada hari Galungan umat Hindu ngejot kepada
umat Islam. Inilah
salah satu potret toleransi di Bali yang sudah mendarah daging dan menjadi
lantunan tradisi positif selama ratusan tahun.**

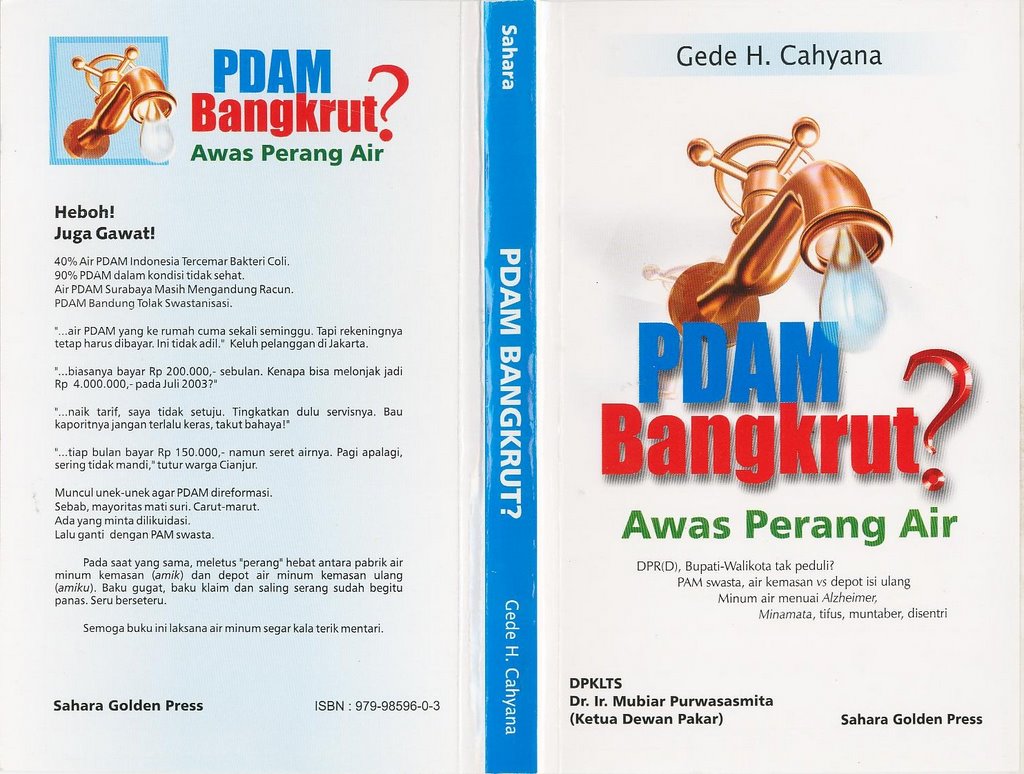
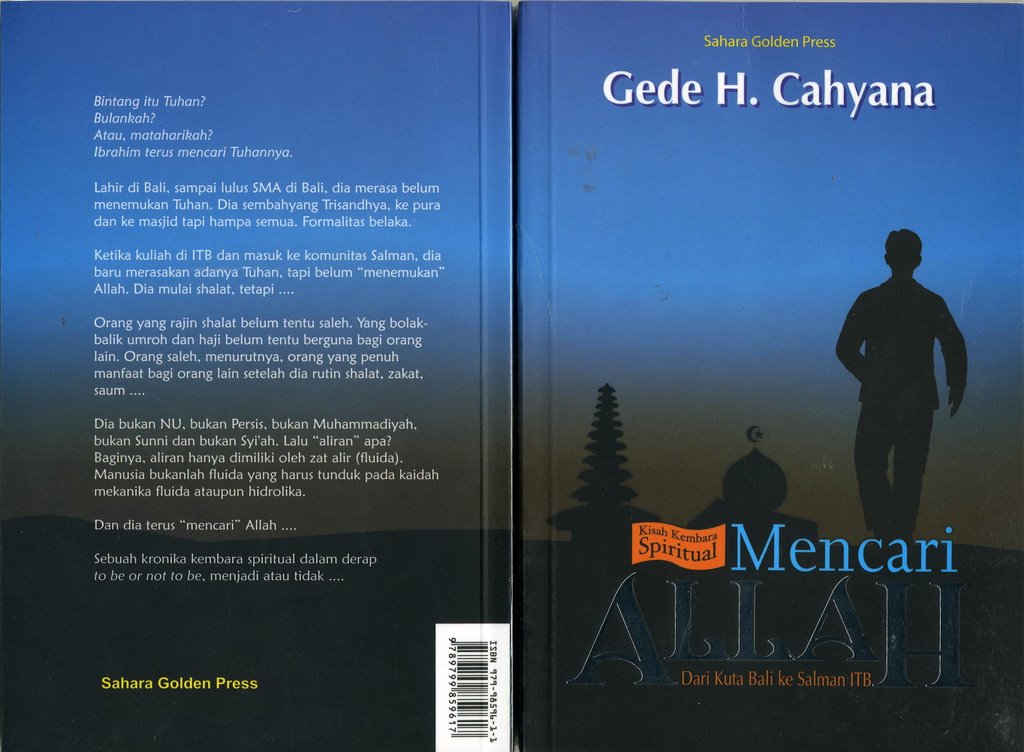
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home