Daging
Tergesa-gesa, hatinya waswas, ia turun dari angkutan kota, di pojok prapatan, dekat tikungan yang menuju stasiun kota. Kresek hitam digenggamnya di tangan kiri, tangan kanannya menenteng tas kanvas. Jam berdetak di angka 23.37 WIB.
Tetesan peluh membasahi dahi, mengalir di alur sisi kanan hidungnya. Tiga gelandangan melihatnya sebentar lalu kembali dalam keasyikan semula.
Masih untung, dalam malam selarut itu, datanglah ojek. Lambaian tangannya pertanda ia butuh jasa antaran. Agak tergesa, ojek langsung menggerung, mengepulkan asap knalpot bercampur debu.
Gelandangan itu terkesima, tidak lama. Mereka serentak lari ke tempat duduk lelaki tadi. Bungkusan. Kresek itu. Gembira sekali mereka karena seharian ini belum makan, perutnya hanya diganjal ubi bekas sisa pedagang gorengan yang mangkal di dekat prapatan itu.
Betapa tidak, kresek itu berisi daging seukuran dua kepalan tangan orang dewasa. Dalam sejam, “pesta” daging asap di dekat jembatan penyeberangan pun dimulai. Lantaran belum makan, suap demi suap masuk ke mulutnya dengan lahap, padahal hanya ditaburi garam dan bawang bekas yang dipulungnya di pasar belakang stasiun.
Betul..., betul sekali, nikmat makan terbukti ketika lapar, apalagi sangat lapar. Tanpa bumbu pun tetap nikmat. Pukul tiga dini hari, mata mereka mulai redup, daging habis, tinggallah bara, abu, asap.
“Maaf pak.., maaf... Bapak lihat kresek saya semalam?” suara lelaki itu.
Sambil menguap dan malas, seorang membuka matanya, “Ya pak, tapi maaf, sudah habis.”
“Habis gimana pak?”
“Itu pak, tadi malam bungkusan bapak sudah kami bakar, kami makan.”
“Astaga..., itu punya ibu saya pak.
Waduh, gimana nih?”
“Iya pak, kami minta maaf. Perut kami lapar sekali!” sahut yang seorang lagi. Semuanya terbangun mendengar percakapan itu. Adzan Shubuh mulai terdengar sayup-sayup.
“Semalam kami lapar pak. Tapi sekarang sudah kenyang. Bapak penolong kami. Terima kasih ya pak.”
Di sudut mata lelaki itu membulir air mata dan berkaca-kaca.
Ada orang yang jauh lebih malang daripada dirinya yang sedang ditimpa ujian. Ia ingat ibunya yang sedang terbaring di rumah sakit dan ingat juga pada nasib gelandangan itu. Tetes pertama akhirnya jatuh membasahi tanah berdebu, galau hatinya melihat nasib tiga orang itu.
“Pak, maaf pak, tolong ikhlaskan daging itu ya, sudah kami makan!” pinta yang tertua.
“Oh.., iya pak.. iya.. saya ikhlas. Tapi pak..., itu..., ibu saya sakit pak. Dan daging itu... itu daging tumor di rahim ibu saya. Kemarin malam dioperasi. Saya bawa pulang, mau dikubur di belakang rumah.“ *
-**-
Daging. Seonggok daging. Bisa bermanfaat, bisa juga mudharat. Ketika banyak orang di pesta pernikahan, ultah, peresmian kantor, dll membuang-buang daging, ada sekitar 70-an juta orang Indonesia yang belum tentu makan daging dalam setahun, kecuali saat Idul Adha. Pada 27 November 2009 lalu sebagian mereka sudah makan daging “normal” lagi.
Kenapa “normal”? Sebab, mereka terbiasa makan daging bekas, daging pulungan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Bahayanya lagi, daging bekas ini ada yang diolah lagi kemudian dijual ke sekolah-sekolah atau ke warung nasi.
Namun, inilah hidup. Banyak orang yang berlimpah uang dengan mudah membeli daging, bisa dimasak sendiri atau beli yang sudah jadi di warung nasi, restoran, rumah makan, dll.
Tetapi, boleh jadi kualitasnya tak jauh beda dengan daging tumor atau lebih buruk lagi karena direndam di dalam formalin atau zat pengawet lainnya. Atau haram karena zatnya, karena cara menyembelihnya, atau karena cara mendapatkannya.
Ingatlah saya pada ucapan khalifah rasyidin, khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, r.a, ”Jangan jadikan perutmu seperti kuburan hewan.” Allahu ‘alam, Allah sajalah yang Mahatahu. ***

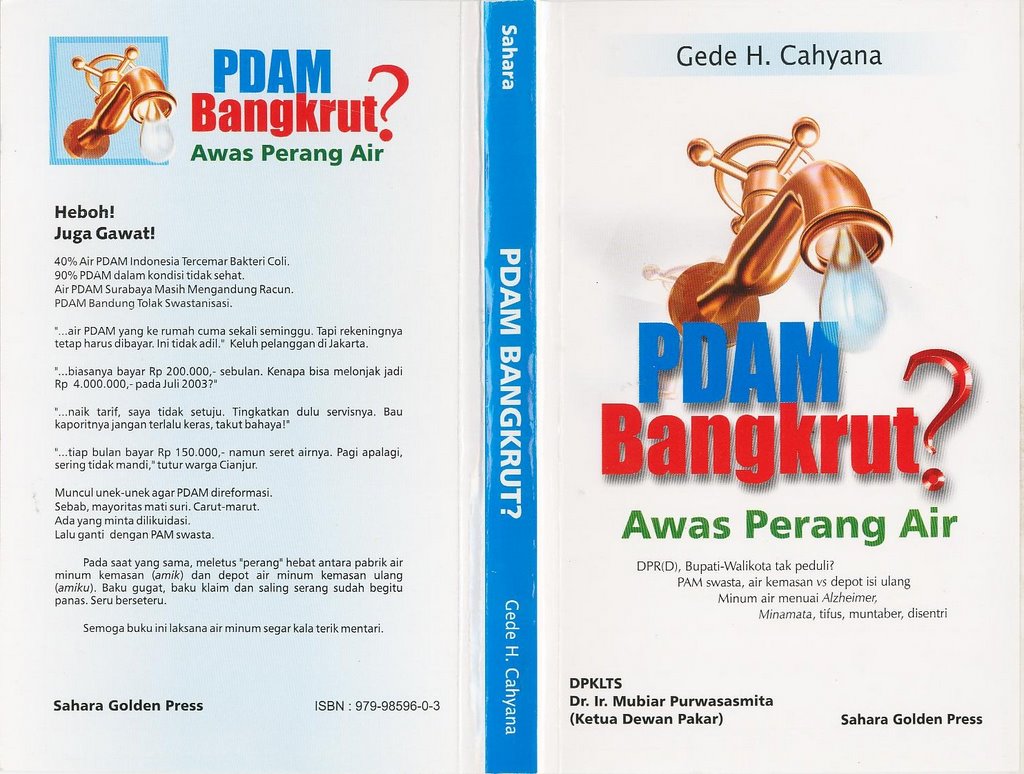
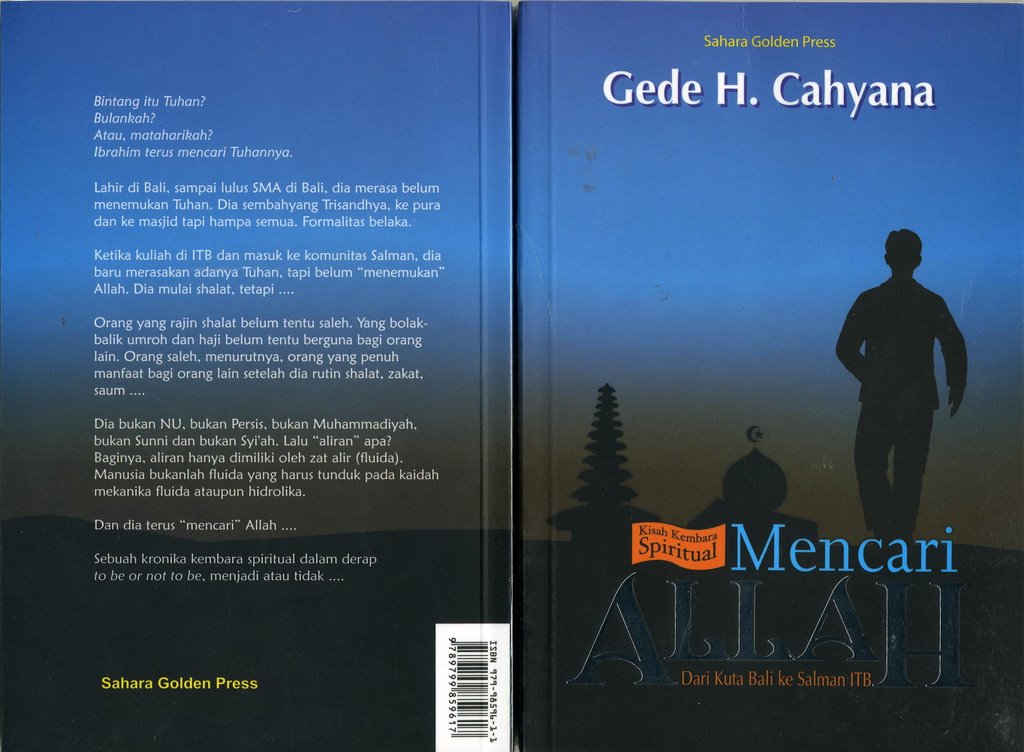
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home