BATIK
Unesco akhirnya menetapkan salah satu produk budaya, yaitu batik sebagai milik Indonesia dan menjadi warisan dunia. Sebagai rasa syukur, pemerintah mengajak masyarakat Indonesia untuk mengenakan batik pada Jumat, 2 Oktober 2009. Dapat dimaklumi rasa bungah pemerintah lantaran beberapa bulan terakhir ini sejumlah produk budaya Indonesia diaku-akui sebagai milik negeri jiran.
Yang mengaku orang Indonesia nyaris tak ada yang tak tahu batik. Bisa dipastikan, minimal bisa diduga, setiap orang dewasa di Indonesia, pasti punya batik. Malah anak-anak TK dan murid-murid sekolah pun diwajibkan mengenakan batik. PNS apalagi, setiap tanggal 17 selalu upacara dan berseragam batik. Mantan presiden masa Orde Baru, Pak Harto dan keluarga besarnya, dikenal sebagai pencinta (bukan pecinta) batik. Waktu puluhan kepala negara bertandang ke Tapos, semuanya mengenakan batik yang didesain oleh desainer nomor wahid di Indonesia. Batik telah membadai budaya yang menyapu semua lapisan masyarakat, mulai dari strata rendah sampai tinggi. Oleh sebab itu, batik bukanlah milik stratum tertentu melainkan kosmopolitan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangihe hingga Rote terbentang kriya budaya turun-temurun ratusan tahun ini.
Lain batik, lain pula komentar orang terhadap yang berbaju batik (pebatik). Faktanya, pebatik belia, di bawah 25 tahun, sering dicap sebagai peselera tua. Pebatik berusia likuran awal selalu diidentikkan sebagai pelawan jeans belel robek di sana-sini, tak pernah dicuci. Makin jarang dicuci makin “saktilah” denimnya. Dulu, pada dekade 1980-an, yakni sebelum Cihampelas Bandung dibanjiri produk jeans belel, kalangan muda sengaja melubangi Levi’s, Lee, JM, Grafitti, Tira, dll yang baru saja dibelinya lalu direndam di air kaporit. Esoknya, muncullah jeans belel “sakti mandraguna”, dipamerkan di antara rekan-rekan pesuka Sersan Grung-Grung bermotor trail sambil trek-trekkan. Dunia terasa milik mereka, layaknya anggota band musik cadas.
Batik, meskipun ada di mana-mana di Nusantara ini, yang sering dinisbatkan sebagai kota batik adalah Solo dan Pekalongan dengan ratusan ribu pembatik, perajin batik. Belum lengkap wira-wiri seseorang di Solo kalau belum menelusup di sela-sela Klewer. Mulai yang dijual kodian sampai eksklusif pun bisa diperoleh, juga bisa dipesan dengan harga bersaing. Beberapa merek terkenal pun ditawarkan di galeri dengan harga kompetitif. Malah ada orang yang kecanduan batik, khususnya batik tulis, sehingga ke mana saja berkunjung selalu saja membeli kain bermotif khas daerah tersebut lalu dijadikan koleksi, ditinggal di lemari. Sesekali saja dikenakan. Adiksi ini, sebut saja dengan istilah Batikaholic atau Batikaholism. Ketagihan batik. Sejak ditetapkan oleh Unesco pada 2 Oktober 2009 nanti, Batikaholik berpeluang masuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Batik, agar tidak dijarah dan diaku-akui sebagai hasil olah pikir dan kreasi bangsa lain, seyogyanya (“sesolonya?”) dipatenkan dan ditulis di dalam KITAB. BATIK – KITAB. Bolak-balik, alternating words. Karena Unesco telah memulainya dan kita sering mengenakannya, maka, berbatiklah pada 2 Oktober 2009 dengan sukarela, sukaikhlas, sukabatik. Berbatik ke masjid saat shalat Jumat pada 2 Oktober itu menjadi salah satu apresiasi atas produk dalam negeri. Teringat pada film seri di TVRI pada dekade 1980-an: ACI, Aku Cinta Indonesia*
Koran Pikiran Rakyat tadi pagi menulis tentang batik. Bagian prolognya bercerita tentang batik yang dikenakan oleh Prof. Dr. Iftikar Z. Sutalaksana ketika mempertahankan disertasinya di Eropa. Tidak seperti lazimnya semua mahasiswa di Eropa yang berjas, baik bule maupun nonbule, Pak Iftikar justru minta izin untuk mengenakan batik ketika ujian disertasinya. Promotornya mengizinkan, lantas..., dekannya pun akhirnya mengiyakan. Jadilah beliau sebagai orang pertama di Eropa, mungkin juga di dunia, yang berbatik ketika sidang doktoral. Bahkan, batik bersejarah itu, masih disimpannya hingga kini. (Ingat Pak Iftikar, jadi ingat kota Roseto dan sepenggal ayat: “Wahai nafsu (jiwa) yang tenang, Al-Fajr: 27. Paparan elaborasi terhadap loncatan teknologi dan kegamangan jiwa manusia pada era nanoteknologi ini, menjadikan manusia seolah-olah onggokan daging yang bergerak, berserak melata, tak beda dengan primata, menjadi asfala saafiliin: jauh lebih hina ketimbang hewan.

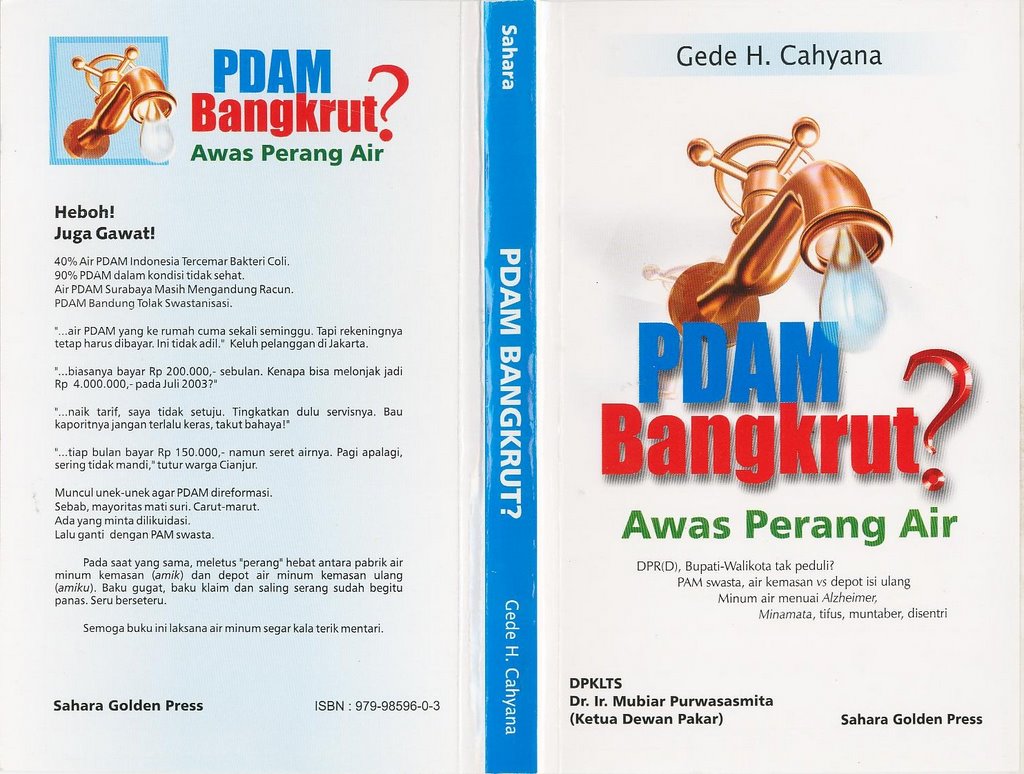
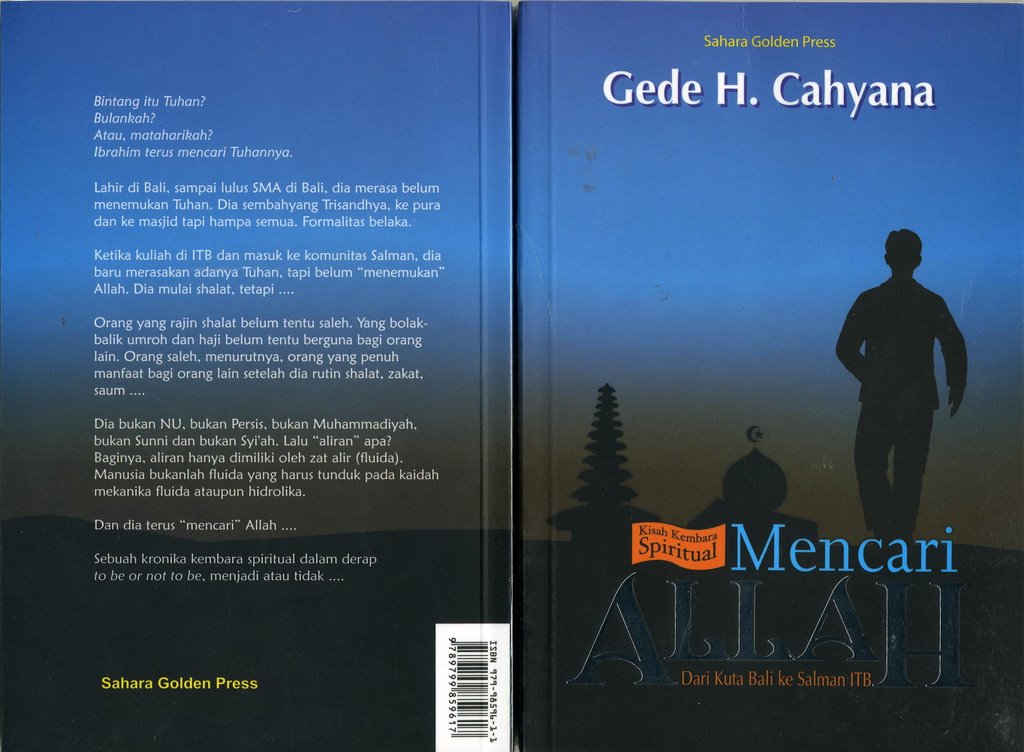
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home