Stress...., Puasa dan Idulfitri?
Di bidang psikosainstek, Stewart Wolf dan John G. Bruhn menjadi orang pertama yang mendalami kajian tersebut di Roseto, Amerika Serikat. Dalam laporan risetnya, Bruhn menyatakan, “… family and community support is disappearing. Most of the men who have hearth attacks here were living under stress and really had nowhere to relieve that pressure …. These people have given up something and it’s killing them.” Sebelum itu, yaitu tahun 1961, Bruhn justru memperoleh hasil yang oposif dan menyatakan bahwa masyarakat Roseto terbaik dalam kehidupan sosialnya sehingga disebut kota ajaib (miracle city).
Tak bisa disangkal, kemajuan sainstek mengantar manusia ke puncak pencapaiannya sekaligus meminggirkannya ke bibir jurang ketegangan dengan ujung psikosomatis. Puasa Ramadhan ditawarkan oleh Al Khalik untuk menetralkan dampak buruk sainstek lewat al Baqarah 183, agar manusia menjadi orang yang memasrahkan hidupnya kepada Allah dan hidup sehat. Menurut organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization), sehat adalah state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. Sehat ialah keadaan sejahtera jasmani, rohani, dan sosial, tak hanya tanpa adanya penyakit atau kelemahan saja. Agar bisa disebut orang sehat harus dipenuhi tiga syarat: jasmani, rohani, dan sosial. Aspek kesehatan sosial ini nyaris diabaikan oleh masyarakat tetapi justru menjadi sebab utama sakit jasmani dan rohani.
Ada sejumlah sebab yang menimbulkan ketegangan (stress) dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, lima di antaranya, menurut Achmad Mubarok (Jiwa Dalam Al Qur’an) sbb:
1. Cemas. Rasa ini muncul karena kehilangan makna hidup. Secara fitri manusia punya kebutuhan akan makna hidup yang hanya bisa dimiliki oleh pejuang yang menyumbangkan sesuatu untuk orang lain. Orang-orang cemas biasanya mengikuti trend dan tuntutan sosial yang belum tentu benar. Sesekali saja dia merasakan kenikmatan sekejap yang palsu. Akibatnya terjadilah gangguan jiwa. Puasa Ramadhan diharapkan menjadi kawah Candradimuka bagi insan-insan cemas ini.
2. Sepi. Ini muncul karena hubungan silaturahmi sudah tidak tulus lagi tetapi memakai topeng-topeng sosial yang palsu sehingga hubungan menjadi gersang, mengidap rasa sepi yang kronis padahal berada di keramaian. Tak bisa menikmati senyum orang lain sebab dianggap topeng belaka seperti ketika dia tersenyum kepada orang lain. Pujian dipandangnya sebagai basa-basi belaka.
3. Bosan. Inilah akibat rasa cemas dan sepi yang berkepanjangan. Hidupnya tak bergairah. Jiwanya kosong, mirip orang yang bermobil mewah tetapi jiwanya becak; berponsel tapi memakai bahasa isyarat tangan. Makan makanan merek luar negeri tetapi wawasan gizinya masih oncom (tak berarti oncom tak bergizi lho, ini sekadar misal). Harta, tahta, dan jabatannya tinggi tetapi jiwanya hampa. Semua atribut, simbol, gelar, baju, sepatu, dasi, ponsel, mobil, cincin, arloji, rumah, dan banyak lagi yang lain tampak modern namun pikirannya tidak menguasai ilmu-teknologi. Di pentas nikmat sekejap, sampai di rumah dia cemas dan sepi kembali. Lantaran bosan inilah dia masuk ke lingkaran narkoba, bunuh diri, racun diri atau gantung diri.
4. Perilaku menyimpang. Kalau rasa cemas, sepi dan bosannya terus menggayut, maka dia mudah melakukan perilaku buruk tanpa sadar seperti merampok padahal dia tak butuh uang, memperkosa tanpa tahu siapa yang diperkosa, membunuh tanpa ada sebab kenapa harus membunuh sehingga hidupnya menjadi semrawut. Bisa juga ia memamerkan foto-foto seronoknya atau bahkan video pornonya ke khalayak, misalnya lewat internet.
5. Psikosomatik. Empat hal di atas jika terus terjadi dapat menyebabkan sakit fisik, sakit lantaran faktor jiwa dan sosial. Menjadi psikosomatik yang dalam bahasa Arab disebut nafs jasadiyah atau nafs biolojiyah. Yang sakit jiwanya, tapi dalam ujud sakit fisik. Makanya, dia selalu mengeluh jantungnya berdeba-debar tanpa sebab, merasa lemah, tak enak badan atau tidak bisa konsentrasi dan sakit maag (tukak lambung).
Salah satu hikmah Ramadhan, jiwa-jiwa kotor itu masih bisa disucikan dengan riyadhah al nafs atau tazkiyah al nafs seperti infak (zakat, zakat fitrah), shalat, kesucian seksual rumah tangga, dan bergaul yang santun secara lisan dan perbuatan.
Selamat saum Ramadhan.
------------------------------------------------------------
Oleh Bambang Q. Aness
SEPULUH hari terakhir seharusnya adalah saat menemukan pengalaman rohani (lailatulqadar) yang digambarkan penuh berkah "seribu bulan", situasi yang dipenuhi pasukan malaikat yang datang membawa kedamaian bagi manusia takwa. Namun, seperti lazimnya tahun-tahun lalu, malam akhir Ramadan adalah malam-malam sepi, jemaah masjid semakin "maju" (tinggal saf terdepan). Simpulnya, saya lebih sibuk memikirkan mudik dan baju baru daripada lailatulqadar. Astagfirullah....
Sepuluh hari terakhir Ramadan memang benar-benar terasa berat. Terutama membayangkan macetnya jalanan mudik dan harga-harga yang melambung tinggi. Kerap muncul pikiran seperti ini, "Andai saja, Idulfitri tak harus mudik dan tanpa ada perayaan tentulah situasinya tidak akan seperti ini." Serentak muncullah kekesalan terhadap Idulfitri, lalu di mana semua sukacita penyambutan Ramadan yang pernah saya lakukan? Kalau dulu saya pernah menyambutnya dengan sukacita, seharusnya sekarang adalah saat berdukacita karena berpisah dengan Ramadan?
Imsak dan madrasah takwa
Ramadan atau imsak adalah saat "pengendalian hawa nafsu". Ramadan adalah madrasah takwa, suatu sekolah yang mengajari pengendalian diri. Namun -- kalau kita hendak jujur -- kita telah mengubah Ramadan menjadi bulan penuh kemanjaan. Bulan yang menyulap kita menjadi merasa berhak dimaklumi oleh banyak pihak lain, bulan yang membuat kita menoleransi diri dalam kemalasan. Padahal, "menjadi takwa" adalah menjadi subjek yang proaktif memberikan pembebasan, kebahagiaan, dan sukacita pada banyak pihak. Lalu, kualitas takwa seperti apakah yang akan kita raih bila selama berpuasa kita justru melatih kemanjaan, bukan melatih menjadi subjek anfa'uhum linnas (yang memberi manfaat bagi pihak lain).
Ya, Ramadan diam-diam telah diubah oleh kita sebagai bulan penuh dengan hawa nafsu. Terutama pada hari-hari akhir ini. Lihatlah, betapa panjang antrean orang yang telah berlelah payah menahan makan dan minum lalu merasa berhak mendapatkan baju baru. Semua toko memproduksi "mesih hasrat", mesin yang membuat hasrat kita untuk memiliki semakin meluap-luap, melalui iklan atau tulisan obral.
Akan tetapi, betapa bebalnya saya. Di tengah kemanjaan itu, saya masih juga merasa berhak mendapat rahmah, magfirah, dan keterbebasan dari siksa panas neraka. Padahal, seorang sufi pernah bilang satu rumus rohani, "Allah akan memberikan apa yang kamu berikan pada pihak lain." Rumus rohani ini adalah rumus kerahiman air, yang rela turun ke dalam tanah dan tampak dari sisi luar demi menghidupi tanaman. Dalam konteks Ramadan, Allah akan memberikan rahmah, bila kita menyebarkan rahmah pada pihak lain, Allah akan memberikan magfirah-Nya bila kita aktif memaafkan dan memohon maaf pada semua pihak dan Allah akan memberikan pembebasan siksa neraka, bila kita membebaskan sanak saudara fakir miskin kita dari kesengsaraan duniawi.
Pada akhir Ramadan, pada saat semuanya akan dipungkas oleh Idulfitri, saya merasakan kepedihan yang luar biasa. Saya telah melepas kesempatan belajar takwa dari Ramadan, padahal tak ada yang bisa memastikan bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Duh, Rabb, kenapa Ramadan ini tidak juga mengubah hati yang dapat mendorong pada ketakwaan, pada pembebasan fakir miskin?
Baju baru, mudik baru
Keinginan mendapat lailatulqadar membuat kita pantas berduka, apalagi setelah menyadari betapa Ramadan tak juga mengubah ulat diri ini menjadi kupu-kupu takwa. Dan hasrat bertemu lailatulqadar ternyata bertabrakan juga dengan hasrat mudik.
Mudik tak sekadar berlebaran di kampung halaman, demikian ungkap banyak ahli, mudik adalah peristiwa budaya yang sarat spiritualitas. Ya, semuanya itu benar. Akan tetapi yang lebih pasti, mudik juga memberikan ketegangan yang menyita waktu. Ditambah mudik, Idulfitri tak lagi peristiwa penuh kemenangan; Idulfitri tak sekadar bersalaman dengan penuh permohonan maaf. Idulfitri telah menjelma menjadi sejumlah biaya untuk transportasi dan membeli baju baru sebagai bekal kontes di hadapan sanak saudara.
Idulfitri adalah juga baju Baru. Selain ketupat, memberikan zakat fitrah pada fakir miskin (apa pun agamanya). Tindak saling memaafkan, angpaw, baju baru adalah penanda utama keriangan di Idulfitri. Tanpa baju baru, Idulfitri pun tak absah. Maka, kenangkanlah keringat kita yang menetes beberapa pada hari yang lalu di pasar atau di mal (yang dengan murah hati memberi diskon besar) untuk mendapat baju baru.
Dari mana datangnya tradisi baju baru? Memang begitulah sunnahnya, kita harus mengenakan baju bagus pada saat hari kemenangan, Idulfitri. Hanya, yang disunnahkan bukanlah baju baru, melainkan di beberapa pedesaan, anak-anak SD mengenakan baju bukan baju baru. Kalau bukan dari sunnah, berarti ada sumber lain? Ya, sumbernya adalah dari tradisi orang tua yang sedang mendidik anaknya, "Nak, kalau kau khatam puasa akan Bapak berikan baju baru yang kamu suka!" Lalu sang anak berpuasa dengan tangguh sambil membayangkan baju baru menempel di badannya.
Kemungkinan kedua adalah dari tradisi masyarakat miskin. Yaitu mereka yang hanya memiliki satu dua pasang baju yang dikenakan dalam segala momen, tidur memakai baju itu, bermain mengenakan baju yang sama, bersekolah pun masih baju yang itu-itu juga. Tentu saja, baju yang itu-itu saja itu sudah tak jelas apa warna dan baunya, maka pada setiap tahunnya para orang tua membelikan baju baru buat anaknya yang diberikan sekaligus sebagai hadiah kemenangan Idulfitri.
Maka saksikanlah, di beberapa daerah miskin, anak-anak seumuran SD berlebaran dengan mengenakan seragam merah putih, lengkap dengan topinya atau mengenakan baju Pramuka, lengkap dengan kacu, peluit, dan baret cokelat -- tentu saja minus tongkat Pramuka. Anak-anak itu begitu bangga mengenakan baju sekolah, di mata mereka ada bayangan keindahan bersekolah dengan baju yang tak sobek-sobek lagi. Di pinggir mereka, orang tua miskin meringis karena miris hanya bisa memberikan baju lebaran yang all in one.
Mari kita bandingkan dengan diri kita yang memiliki baju berlemari-lemari, itu pun masih juga merasa perlu menambahi baju baru pada Lebaran ini. Atas fenomena ini, kita dapat merenung kembali ihwal puasa kita. Puasa Ramadan adalah madrasah takwa, yang mengajari kita bersolidaritas pada orang lain -- yang kekurangan -- dan membebaskan mereka.
Salah satu stimulus dari Tuhan adalah sejumlah pahala dan ibadah tambahan. Misalnya memberi makan berbuka bagi fakir miskin akan mendapat pahala satu orang berpuasa atau berpahala 20 tahun iktikaf. Belum lagi ibadah zakat fitrah yang berfungsi sebagai penyempurna bagi puasa sebulan penuh. Semuanya berfungsi untuk memancing solidaritas abadi, seumur hidup. Jadi zakat fitrah itu, kira-kira, bisa disamakan dengan peletakan batu pertama dari bangunan ukhuwah islamiyah.
Bila kita masih saja memikirkan diri sendiri, jangan-jangan kita tidak lulus dari madrasah takwa bulan Ramadan? Bila kita masih marah karena lupa membeli baju baru, jangan-jangan tadarus kita tak sampai pada Q.S. Al-A'raf ayat 26 tentang baju takwa.
"Baju takwa" (libasut taqwa) ini, menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, adalah perangai yang baik, dengan "Makrifat akan menjadi modal utamanya, pengendalian diri sebagai ciri aktivitasnya, kasih asas pergaulannya, kerinduan kepada Ilahi tunggangannya, zikir pelipur hatinya, keprihatinan adalah temannya, ilmu senjatanya, sabar busananya, kesadaran akan kelemahan di hadapan Allah kebanggaannya, zuhud (tidak terpukau oleh kemegahan duniawi) sebagai perisainya, kepercayaan diri menjadi harta simpanannya dan kekuatannya, kebenaran sebagai andalannya...." Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik (QS 7:26).
Meraih keikhlasan
Semua keluhan ini adalah bukti betapa saya tak bisa ikhlas menerima perintah Ramadan. Kalaulah saya ikhlas, pastilah tak ada alasan untuk memanjakan diri; kalau ada keikhlasan di hati ini, tak ada ruang bagi keluhan menyediakan biaya mudik atau baju baru. Keikhlasan itu, konon, seperti air suci yang meluap-luap yang menyingkirkan seluruh luka hati (rasa kesal atau dendam, rasa tidak puas atau ingin dipuji).
Amal yang dilakukan dengan ikhlas -- menurut para sufi -- akan memiliki kekuatan untuk terbang ke langit menghadap hairat Allah untuk Dia nilai. Sebaliknya, amal yang tidak ikhlas, akan tetap tinggal di bumi (hanya dinilai atau dihargai manusia). Lalu amal yang ikhlas itu akan dapat menurunkan balasan (jaza') dari Allah. Mumpung ada satu dua hari lagi, saya mau belajar ikhlas.
Sebelum Ramadan berakhir, selagi masih ada sisa satu dua hari, mudah-mudahan kita dapat melengkapi diri dengan keikhlasan. Mudah-mudahan masih tersedia lailatulqadar yang membuat kita mendapat predikat Aidin (orang yang kembali pada fitrahnya) dan Faizin (pemenang yang telah mengendalikan hawa nafsunya menjadi takwa).
Selamat Idulfitri, selamat menuai takwa!

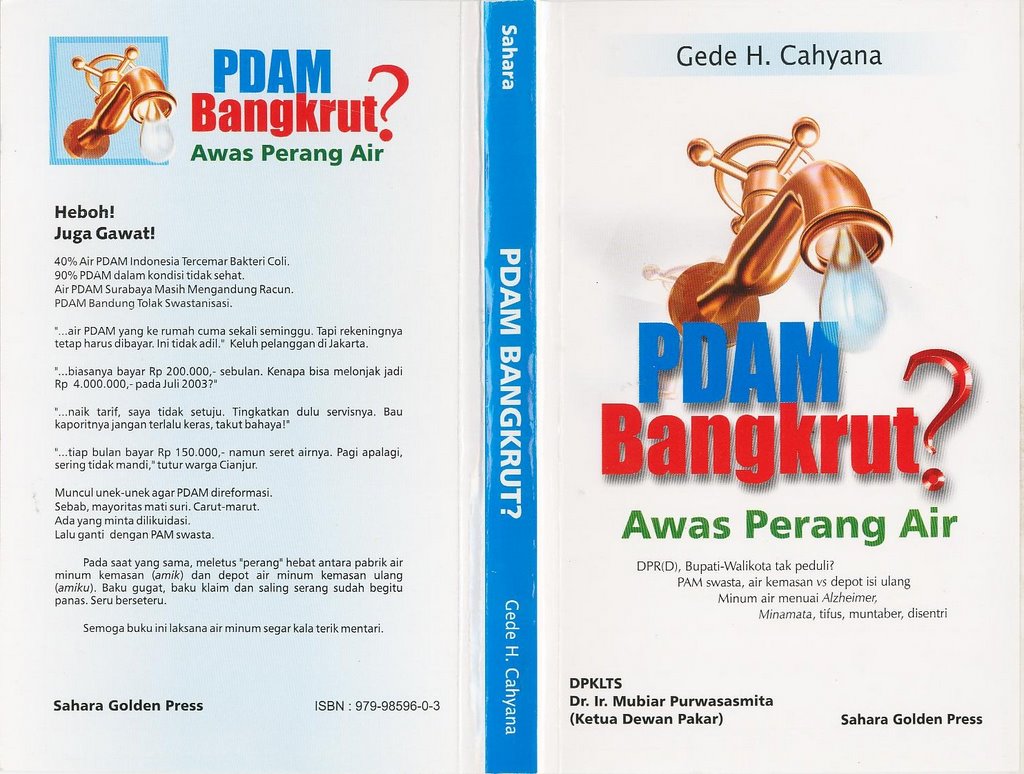
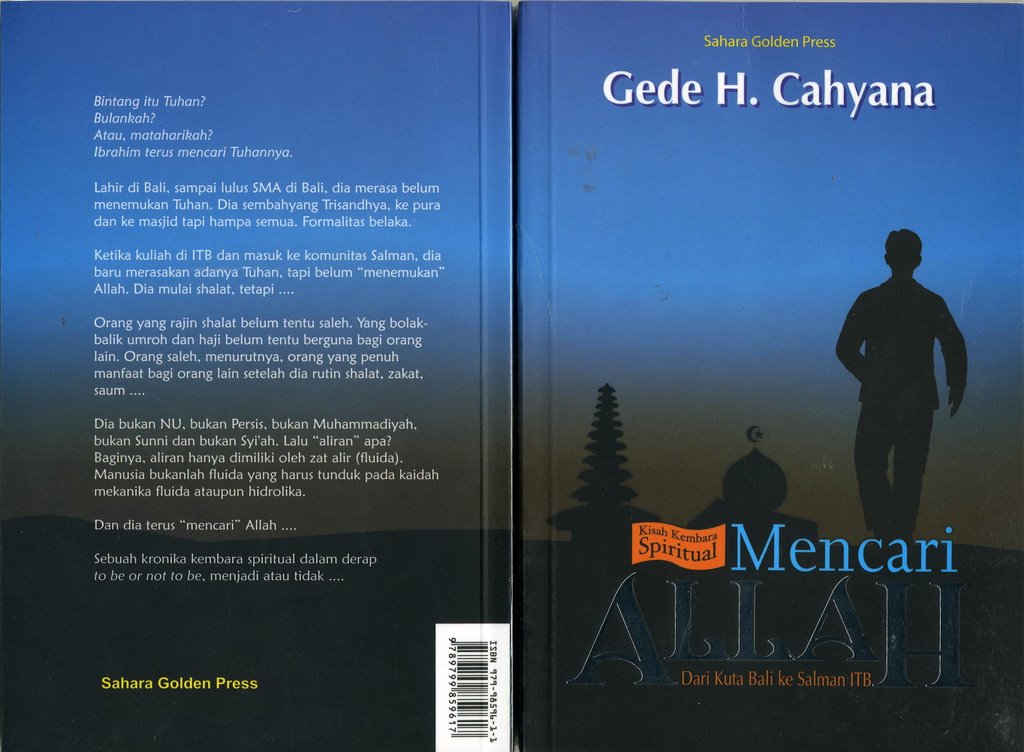
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home