Bibliophobia, Bibliolabbeling
Di Australia, menurut berita radio ABC Senin, 11 Juli 2006 lalu, ada dua buku yang dilarang beredar, bahkan di-sweeping lantaran diduga berbau jihad. Bagi pemerintah negeri kanguru itu, jihad identik dengan teroris. Padahal jihad punya banyak arti, termasuk dalam arti bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan. Serius bekerja, serius berbagi kebaikan-kebenaran pun adalah suatu bentuk jihad. Salah persepsi, salah tanggap atau paranoid dalam memandang Islam berdampak pada peminggiran Islam. Pemarjinalan pun terjadi dalam bidang akademik dengan cara memperalat orang Indonesia yang studi di sana, baik S1, S2, maupun S3. Tak sedikit didikan mereka justru akhirnya mencabik-cabik Islam, bak menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, ular berkepala dua.
Kasus pelarangan buku memang sering terjadi dan kebanyakan subjektif, termasuk di Indonesia. Bagaimana kasus pelarangan buku dan sweeping di negara kita? Di negara nyiur melambai ini kerapkali sweeping dan pembakaran buku itu langsung menjurus ke toko dan pedagangnya. Dari sudut pandang pedagang, kalau buku-buku yang diduga bermisi jihad itu DIBELI kemudian dibakar oleh pembelinya karena menderita bibliophobia - takut pada isi dan misi buku-, atau bibliocast - sangat puas setelah memberangus buku -, tentu tidak masalah karena labanya sudah di tangan. Namun demikian, ada juga yang tidak setuju atas cara tindak seperti itu karena cintanya begitu besar pada buku, tak sekadar jadi jembatan jual-beli, tak sekadar uang. Mereka baru akan memasalahkannya kalau terjadi perampasan hak milik tanpa transaksi jual-beli yang adil.
Pandangan penulis buku, lain lagi. Meski ada yang kecewa pada aksi sweeping, tak sedikit penulis yang senang karena oplahnya bertambah, diburu para kolektor buku. Penerbit pun ketiban pulung, bahkan berancang-ancang mencetaknya lagi. Ini tentu saja kalau belum resmi dilarang oleh pemerintah setempat, tetapi hanya aksi sweeping dari ormas saja. Para pembajak buku pun bahkan ikut ambil ancang-ancang dan menyiasati pasar demi uang “ilegal”. Itu sebabnya, sejumlah buku yang dilarang biasanya mampu bertengger di puncak penjualan selama mungkin. Satanic Verses-nya Salman Rushdi adalah kasus yang melegenda. Sebetulnya, jika disikapi dengan kepala dingin, para pakar di bidang studi Islam dan keislaman dapat melawannya dengan buku tandingan. Buku hujatan dan buku tandingan itu bisa dibahas dalam seminar dan hasilnya sudah pasti, buku hujatan bakal terhujat dan terhinakan secara alami atas semua kedustaannya. Sebaliknya Islam akan makin diterima masyarakat karena ajarannya yang membawa rahmat bagi alam.
Selain Satanic Verses, ada juga The Da Vinci Code yang telah diangkat ke layar lebar (Seek The Truth, Seek The Codes) dibintangi Tom Hank dan Audrey Tautou. Hanya saja, karya Dan Brown itu tak bernasib seperti Satanic Verses dan dia nyaman-nyaman saja. Di mancanegara seperti itu. Di Indonesia tak jauh beda. Sebagai penyakit buku, - bibliofobi dan bibliokas - pernah pula terjadi pada masa Orde Baru. Saat itu ketakutan teramat sangat pada sejumlah buku yang dianggap mampu mengubah pola pikir masyarakat menghantui penguasa. Karenanya, dengan alasan kamtibmas yang stabil, dinamis dan terkendali (tiga kata yang paling populer waktu itu), banyaklah buku yang dilarang beredar. Bahkan yang disimpan pembeli pun wajib diserahkan ke kepolisian atau kejaksaan. Kalau tidak dan membandel, undang-undang subversi telah menunggu dan bisa mengantarnya ke balik jeruji bui. Pada masa itu, jarang yang berani memiliki buku "pelat merah" itu. Jangankan buku-buku kiri, buku-buku atau selebaran terbitan kelompok Petisi 50 atau Komando Jihad dan kelompok yang dinamai GPK (Gerombolan Pengacau Keamanan) pun banyak yang takut-takut memegangnya.
Karena itulah, pemerintah, pemuka agama, penulis dan penerbit buku, akademisi dan rakyat awam sekali pun agar mau memosisikan dirinya sebagai wadah penyalur aspirasi dan inspirasi keilmuan dari mana pun datangnya, apa pun topiknya. Dengan cara ini diharapkan kita punya solusi alternatif yang adil (win-win solution) sekaligus menjaga nalar bangsa agar tetap meningkat tinggi sehingga mutunya tidak melata di bawah negara-negara lain. Terlebih lagi kita tahu, tak kurang dari 85% rakyat Indonesia sudah melek huruf meski minat bacanya (apalagi tulisnya) masih tipis. Justru karena itulah kita perlu memberikan kebebasan berekspresi baca-tulis kepada setiap orang. Dengan demikian, tidak boleh ada pencekalan terhadap produk intelektual khususnya buku dan berilah kebebasan mengkajinya di setiap seminar atau pun temu ilmiah formal-informal lainnya tanpa rasa curiga. Malah polemik dan debat tentang isi buku akan membiasakan kita menata argumentasi apik yang bertanggung jawab. Seandainya tidak sependapat, jawablah dengan buku lagi. Pendeknya, tulisan dijawab dengan tulisan, bukan dengan kekuatan otot dan pemberangusan kalau tak ingin disebut menderita bibliofobi.
Bibliolabelling
Ketika segmen konservasi lingkungan mengenal istilah ecolabelling, produk makanan minuman mengenal istilah halallabelling (mestinya ada label haram juga yang diterakan eksplisit) dan obat-obatan mencantumkan jenis zat kimia dan kadarnya (compolabelling), maka daripada sweeping atau pembreidelan, lebih bernas dan elegan pemerintah suatu negara mewajibkan setiap penerbit mencantumkan label jenis buku atau bibliolabelling. Cara ini membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyeleksi sendiri kebutuhan bacanya. Bacaan yang baik dan wajar sesuai nalar tentu akan dibeli dan bahkan dicetak berkali-kali, sedangkan yang tak menawarkan sesuatu yang diminati konsumen akan tidak ditengok. Janganlah kesiapan nalar dan tingkat pendidikan masyarakat dijadikan alasan karena hal ini akan berkembang paralel dengan peningkatan kemauan bacanya. Inilah yang bakal meramaikan kancah dunia buku, dunia tatatulis yang masih sepi ini.
Selain sesuai dengan HAM dan HaKI, pelabelan buku itu pun mengharuskan semua penulis dan penerbit berlaku jujur. Misal, pelabelan bisa menurut subjek agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha atau komunis dll. Hanya saja patut diingat dan wajib jujur agar jangan sampai buku berlabel agama tertentu berisi propaganda yang justru mendiskreditkan agama tersebut dan ditulis oleh penulis yang bukan beragama bersangkutan. Kebohongan atau kamuflase seperti ini justru makin memperkeruh kebebasan berpendapat. Contoh lain, segmentasinya berdasarkan bidang ilmu dan teknologi atau humaniora seperti label lingkungan, kimia, fisika, sosiologi, psikologi atau kedokteran. Isi kelompok buku ini sebetulnya bisa ditilik dari judulnya karena buku yang tergolong textbook (buku-induk), tanpa label pun orang sudah tahu. Tapi tidak demikian dengan buku populer apalagi sastra yang perlu interpretasi dari pembacanya.
Sekali lagi, yang terpenting dari bibliolabelling adalah kejujuran. Jangan ada penipuan atau kebohongan publik di sini. Artinya, judul buku dan labelnya harus mencerminkan isinya. Tidak boleh ada plintiran isi yang mengecoh konsumen. Kalau ini terjadi, haruslah dimejahijaukan dan pelanggarnya dihukum setimpal sedangkan bukunya direvisi atau diluruskan dan disebarkan lagi. Buku bermasalah tadi tetap jangan dimusnahkan, tapi biarkan saja sebagai dokumen sejarah yang “abadi” hingga kiamat tiba. Kalau ada kebohongan atau kepalsuan atau katakanlah propaganda murahan maka lambat atau cepat akan ketahuan juga. Sejarah akan bicara jujur di kemudian hari dan pasti mengungkapkan kebenaran.
Jadi, janganlah fobi buku seperti di Australia dan negara barat terjadi di sini (lagi) termasuk janganlah meniru perilaku pasukan perang abad pertengahan mereka yang membakar habis literatur dan perpustakaan universitas di dunia Arab. Janganlah takut pada buku karena kalau demikian berarti para penakut itu memang punya atau paling tidak, dia merasa bersalah pada kebenaran isi suatu buku. Marilah beri kebebasan nalar ini menjalar-jalar dalam ujud buku, apapun temanya, demi membentuk masyarakat-buku. ***
Gede H. Cahyana

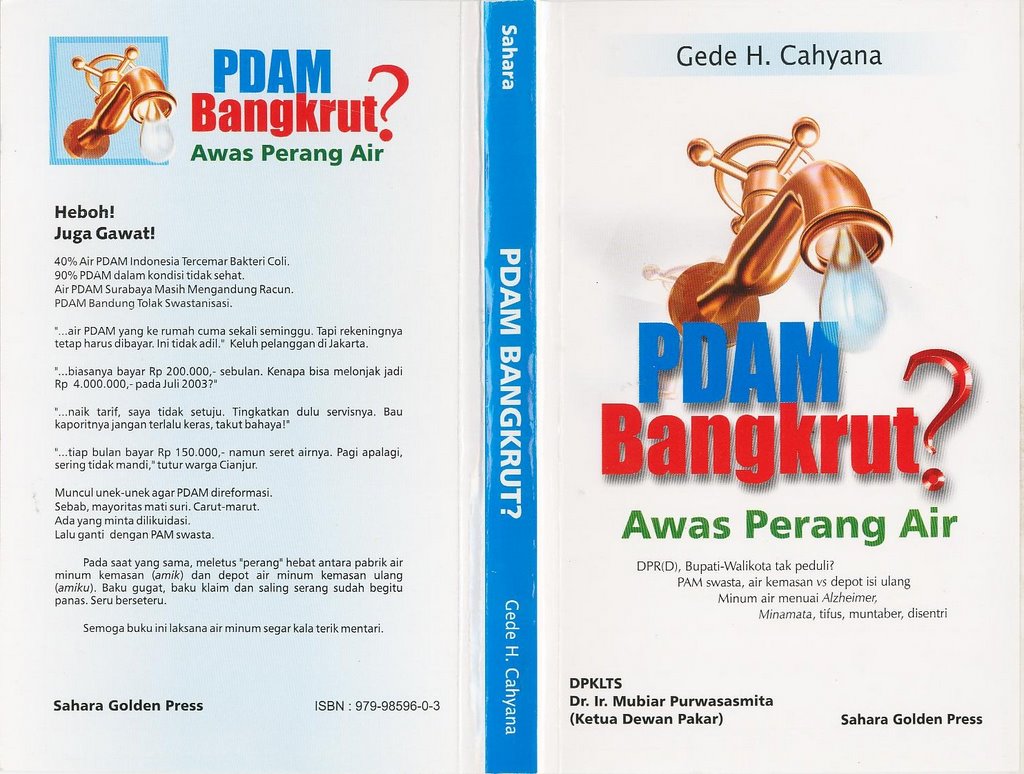
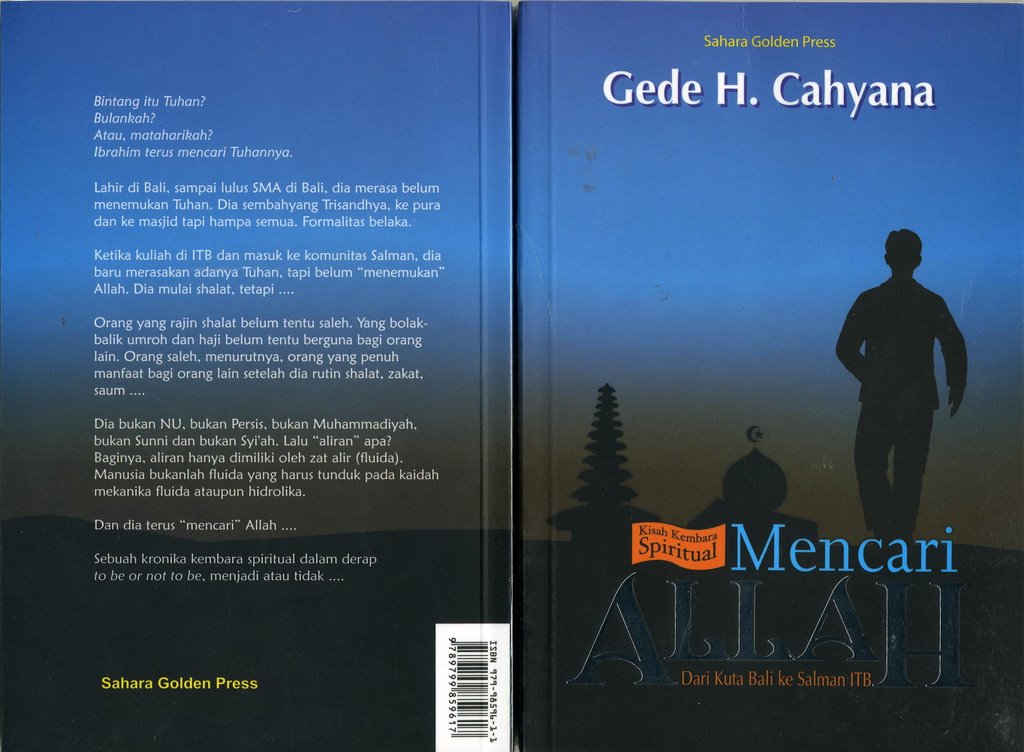
0 Comments:
Posting Komentar
<< Home